Oleh Irvan Mahmud (Direktur Garuda Institute)
Cuaca ekstrim di Indonesia terus berulang: banjir, kekeringan, dan anomali musim menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang membentuk ulang risiko sistemik. Ia sistemik karena mempengaruhi produksi pangan, pasokan energi, penurunan keandalan infrastruktur, krisis air bersih, kerusakan struktural pesisir, pulau panas perkotaan (urban heat island), dan lain-lain.
Negara bertindak setelah bencana terjadi (reaktif), sementara kebijakan mitigasi di hulu untuk mengurangi risiko sangat terbatas. Kebijakan iklim di Indonesia didasarkan pada pendekatan sektoral-fragmentatif. Sementara risiko iklim tidak mengenal single risk authority. Krisis iklim di Indonesia juga soal ketimpangan kebijakan. Wilayah pinggiran dan rentan minim data, minim anggaran, minim kapasitas dan climate finance belum menyentuh akar rumput.
Dari sisi fiskal, kebijakan negara tidak efisien: biaya perawatan infrastruktur akan meningkat, penurunan usia teknis bangunan, dan paling mahal adalah biaya pemulihan pasca bencana seperti bencana di Aceh dan Sumatra pada akhir November 2025. Pendekatan semacam ini juga melemahkan legitimasi negara ketika masyarakat terus-menerus menjadi korban. Tanpa navigasi risiko iklim, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan terus dipaksa menjadi pemadam kebakaran.
Tantangan bagi pemerintahan Prabowo Subianto bukan sekadar merancang program adaptasi sektoral berbasis fisik dan pendanaan. Jauh lebih penting dan mendesak berbasis kebencanaan dengan variabel risiko perubahan iklim sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional jangka panjang. Jika agenda pembangunan tidak memasukkan risiko iklim sebagai prinsip utama, maka pertumbuhan ekonomi berisiko dinikmati secara timpang, kuat di pusat, rapuh di pinggiran dan kelompok yang paling terdampak adalah buruh tani-petani kecil, nelayan tradisional, masyarakat adat, dan kaum miskin yang kontribusinya paling kecil terhadap krisis iklim.
Dengan target swasembada pangan dan energi, hilirisasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, penguatan stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global, perubahan iklim harus ditempatkan sebagai determinan strategis dalam seluruh perencanaan kebijakan.
Agenda swasembada pangan sangat bergantung pada stabilitas iklim. Produksi beras, jagung, bawang, kopi, dan komoditas strategis lain semakin rentan terhadap anomali cuaca. Ketika gagal panen terjadi, negara dihadapkan pada pilihan sulit: impor pangan dan ini berdampak pada neraca perdagangan dan fiskal, atau subsidi besar yang membebani APBN. Tanpa navigasi risiko iklim yang terintegrasi, swasembada pangan berisiko menjadi target politik yang rapuh.
Dalam laporan PI-AREA (2022) berjudul “Dampak Perubahan Iklim Terhadap Sektor Pertanian Indonesia: Fokus Komoditas Padi dan Kopi (Arabika Dan Robusta)”. Riset ini menunjukan bahwa kenaikan permukaan laut dan salinitas telah memengaruhi produksi padi dan kopi. Dengan skenario kenaikan permukaan laut setinggi 1 meter, sekitar 134.509 hektar sawah pesisir (51 persen terletak di pulau Jawa) terendam. Skenario ini akan menghilangkan hampir 1 juta ton produksi beras – setara dengan kebutuhan beras 5 juta orang. Perubahan pola curah hujan dan kejadian iklim ekstrim merupakan faktor dominan yang mempengaruhi produksi padi dan kopi.
Hal serupa berlaku untuk ketahanan energi. Infrastruktur energi terutama pembangkit listrik, jaringan distribusi, hingga kawasan industri semakin terpapar risiko iklim seperti banjir, dan kenaikan muka air laut. Ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi juga oleh ketahanan sistem terhadap gangguan iklim.
Demikian pula dengan agenda hilirisasi dan pembangunan infrastruktur. Kawasan industri, pelabuhan, bendungan, dan jalan dibangun dengan investasi besar, tetapi sering kali belum sepenuhnya mempertimbangkan proyeksi risiko iklim jangka panjang. Banjir, abrasi, dan cuaca ekstrem membuat biaya pemeliharaan dan rehabilitasi naik berkali lipat. Negara kembali membayar mahal karena perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya berbasis risiko iklim.
Lebih jauh, perubahan iklim juga memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas negara (pertahanan). Bencana hidrometeorologi berulang menuntut keterlibatan aparat negara dalam operasi kemanusiaan, logistik, dan pemulihan wilayah terdampak. Dalam perspektif keamanan nasional, perubahan iklim adalah threat multiplier yang dapat memperlemah stabilitas jika tidak terkelola.
*Arah Kebijakan*
Konsep menavigasi risiko perubahan iklim menjadi relevan dan mendesak baik secara strategis maupun politik. Dalam kerangka Prabowonomics, swasembada pangan dan energi, hilirisasi, infrastruktur, dan penguatan pertahanan, bukan semata agenda ekonomi, tetapi prasyarat stabilitas negara.
Kebijakan publik yang masih bergerak dalam logika sektoral harus diakhiri. Kerangka kebijakan harus secara tegas menempatkan risiko iklim sebagai variabel utama dalam pengambilan keputusan pembangunan jangka panjang.
Pertama, risiko iklim harus diintegrasikan secara eksplisit dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan kebijakan sektoral pangan dan energi, hilirisasi, dan infrastruktur. Bukan sekadar pertimbangan.
Kedua, mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI) dengan paradigma perlindungan lingkungan sebagai hak asasi manusia (HAM). Prinsip yang harus diadopsi adalah “keadilan iklim”. Hal ini penting sebab krisis iklim bukan sekedar permasalahan fisik, tetapi persoalan etika, politik, ekonomi, hukum, dan HAM.
Ketiga, navigasi risiko iklim harus berpihak pada wilayah dan kelompok rentan. Misalnya asuransi iklim bagi petani kecil, pendanaan adaptasi untuk wilayah rawan bencana, dan hal mendesak lainnya yang sifatnya perlindungan sosial harus menjadi bagian dari strategi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tidak diperkenankan merusak kelangsungan ekologi. Negara harus hadir sebagai penggerak pertumbuhan, sekaligus pelindung warga.
Keempat, koordinasi lintas sektor diperkuat dengan tugas dan fungsi rigid, dari level pusat hingga daerah. Kemampuan membaca ancaman, mengelola ketidakpastian, dan mengarahkan sumber daya secara strategis tidak bisa ditunda lagi.
Kelima, secara institusional, penegakan hukum harus diperkuat dan memperketat pengawasan guna memastikan nevigasi risiko iklim berjalan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
Sebagai renungan bersama, kita bisa melihat bagaimana sejarah telah menyaksikan bangkit dan runtuhnya banyak peradaban. Menurut antropolog Jared Diamond (2005) dalam karyanya “Collapse”, bahwa peradaban terancam runtuh ketika melampaui batas keberlanjutan lingkungannya.
Pada akhirnya, pemerintahan Prabowo dihadapkan pada pilihan: membiarkan risiko iklim menjadi penghambat pembangunan, atau menjadikannya panduan dalam menata arah kebijakan pembangunan nasional. Menavigasi risiko perubahan iklim bukan sekadar urusan lingkungan, melainkan ujian kepemimpinan politik dalam menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan serta keadilan sosial.
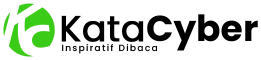
























































Leave a Review